Hari Jantung Sedunia: Strategi Kesehatan yang Efektif
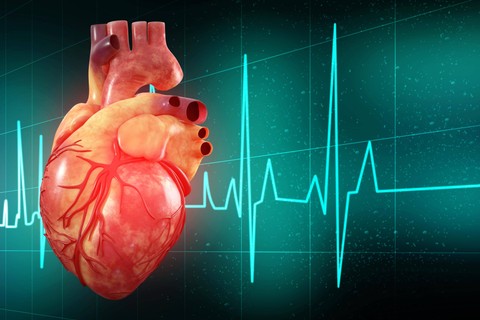
Hari Jantung Sedunia dan Tantangan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah di Indonesia
Hari Jantung Sedunia (World Heart Day/WHD) merupakan inisiatif global yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit jantung dan pembuluh darah (PJPB), termasuk penyakit jantung dan stroke. Inisiatif ini didirikan oleh Federasi Jantung Dunia (World Heart Federation/WHF), sebuah organisasi yang mewakili komunitas kardiologi dan yayasan jantung di seluruh dunia.
Gagasan pertama kali diajukan oleh Dr. Antoni Bayés de Luna, mantan presiden WHF pada periode 1997–1999. Ia menyadari kebutuhan akan kampanye terpadu untuk menghadapi PJPB, yang menjadi penyebab utama kematian di akhir abad ke-20. Awalnya, Hari Jantung Sedunia dirayakan pada hari Minggu terakhir bulan September. Namun, pada tahun 2011, tanggal perayaan ditetapkan secara permanen menjadi 29 September setiap tahunnya.
Salah satu pesan utama Hari Jantung Sedunia adalah bahwa 80% kematian prematur akibat penyakit jantung dan stroke dapat dicegah melalui pengendalian faktor risiko seperti tembakau, pola makan tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik. Tema WHD tahun 2025 adalah “Gunakan Jantung untuk Semua Jantung” (Use Heart for Every Heart). Tema ini mendorong setiap orang untuk memahami risiko PJPB pribadi mereka dan mengambil tindakan proaktif.
Di Indonesia, PJPB bukan hanya ancaman, tetapi telah menjadi epidemi yang memberatkan kesehatan masyarakat dan keuangan negara. Penyakit jantung koroner (PJK) dan stroke seringkali disebut sebagai "pembunuh senyap" karena tidak menunjukkan gejala signifikan pada tahap awal. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 mencatat bahwa prevalensi PJK pada penduduk usia ≥15 tahun mencapai sekitar 1,5%. Sementara itu, prevalensi stroke mencapai 10,9 per 1.000 penduduk.
Penyakit jantung dan stroke sangat berkaitan dengan hipertensi, yang menjadi pintu gerbang PJPB. Data RISKESDAS 2018 menunjukkan bahwa 34,1% penduduk usia ≥18 tahun mengidap hipertensi. Lebih dari sepertiga penduduk dewasa Indonesia berisiko tinggi terkena PJPB. Sayangnya, banyak penderita tidak menyadari kondisi mereka atau tidak menjalani pengobatan secara teratur.
Tren yang mengkhawatirkan adalah pergeseran usia onset PJPB. Dulu dianggap penyakit usia lanjut, kini serangan jantung dan stroke semakin sering menyerang kelompok usia produktif (30-45 tahun). Perubahan gaya hidup, konsumsi makanan cepat saji, merokok, dan kurangnya aktivitas fisik menjadi faktor utama. Selain itu, peningkatan stres kerja, obesitas, dan diabetes tipe 2 pada remaja dan dewasa muda juga turut berkontribusi.
Penyakit jantung dan stroke secara konsisten menduduki peringkat teratas dalam klaim penyakit katastropik. Biaya pengobatan untuk PJPB mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun, memberatkan BPJS Kesehatan. Beban biaya ini mengancam keberlanjutan sistem JKN dan mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pencegahan.
Krisis PJPB di Indonesia diperparah oleh ketidakmerataan fasilitas kesehatan dan SDM. Alat diagnostik canggih seperti Cath Lab hanya tersedia di rumah sakit besar, sementara Puskesmas masih kekurangan pelatihan dan alat deteksi dini. Rasio dokter spesialis jantung terhadap jumlah penduduk Indonesia jauh di bawah standar ideal WHO.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berfokus pada pergeseran paradigma dari pengobatan ke pencegahan. Puskesmas harus menjadi benteng utama untuk skrining dan manajemen faktor risiko. Program Prolanis harus diperkuat agar pasien hipertensi dan diabetes bisa terkontrol.
UU Kesehatan juga mengatur pemerataan tenaga kesehatan dan penggunaan teknologi digital. Telekardiologi dan telekonsultasi spesialis kini memiliki landasan hukum. Penggunaan alat kesehatan dalam negeri dan pengadaan obat esensial juga menjadi prioritas.
Meskipun UU Kesehatan membawa solusi struktural, implementasi di lapangan menghadapi tantangan. Regulasi turunan harus segera disusun, dan koordinasi antar lembaga diperlukan. Penguatan layanan primer membutuhkan peningkatan kapasitas Puskesmas serta investasi dalam pencegahan. Keberhasilan melawan "pembunuh senyap" ini sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam menjalankan regulasi dan memastikan ketersediaan sumber daya.

Posting Komentar